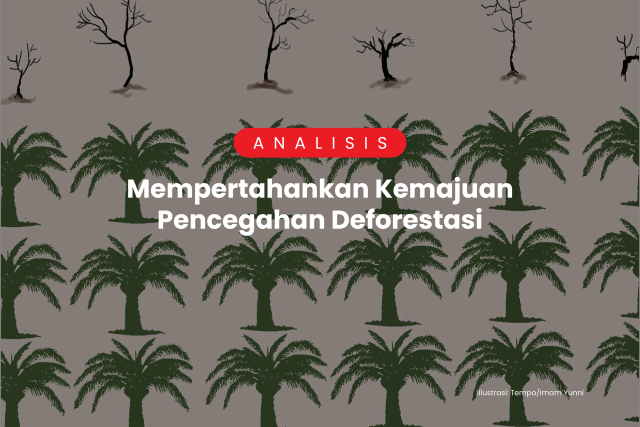

New Mandala, 21 Februari 2022
DPR menyetujui Undang-Undang Ibu Kota Negara pada pertengahan Januari 2022. Ini merupakan satu di antara pembuatan undang-undang tercepat dalam sejarah legislatif di Indonesia, perlu waktu kurang dari dua bulan sejak DPR membentuk komisi khusus pada pertengahan Desember tahun lalu hingga rapat terbuka pada awal 2022. Normalnya proses itu perlu setidaknya enam bulan, tergantung isu dan kemauan politik. Undang-udang tentang ibu kota baru itu mengandung pro dan kontra. Sementara pemerintah dan DPR berharap ia berjalan mulus, tampaknya rancangan undang-undang itu tidak melibatkan aspirasi atau perspektif warga yang ada di lokasi yang diusulkan di Kalimantan. Riset saya mengungkap bahwa suara setempat, khususnya masyarakat adat, diabaikan dari diskusi tentang rancangan undang-undangnya. Lebih dari itu, ada isu penting lain yang muncul dalam hal tumpang tindih dengan aturan-aturan di lokasi ibu kota baru tersebut. Saat ini ada 162 konsesi sumber daya alam di pusat lokasi ibu kota baru dan sekitarnya. Tentu saja, dua pengabaian dari proses ini bertentangan dengan visi ibu kota baru sebagai kota yang cerdas, hijau, indah, dan berkelanjutan.
Satu isu penting yang harus diselesaikan adalah pengakuan hak penduduk asli atas tanah. Meski ibu kota baru akan didirikan di tanah negara, yang meliputi 56.180 hektare untuk area pusatnya dan 199.962 hektare untuk pengembangan di seklelilingnya, area raksasa ini beririsan dengan bagian-bagian tanah yang ada milik penduduk asli. Kesultanan Kutai Kartanegara tidak diundang oleh pengambil keputusan nasional untuk membahas status tanah di lokasi ibu kota baru, walaupun Kesultanan masih mempunyai hak tradisional atas tanah di sana. Sebelum bergabung dengan Republik Indonesia pada 1959, Kesultanan merupakan pemerintahan merdeka yang wilayahnya meliputi teritori Provinsi Kalimantan Timur saat ini. Kesultanan telah memulai lagi kegiatannya pada 1999 setelah vakum 40 tahun. Lokasi itu meliputi pula sejumlah masyarakat asli yang memanfaatkan tanah untuk mencari ikan dan bertani.
Namun, pemilik tradisional ini juga diabaikan dalam diskusi. Salah seorang wakil lokal Kesultanan mengatakan kepada saya bahwa mereka tak pernah mendapat kesempatan untuk membahas proses ibu kota negara dalam diskusi formal maupun informal dari pemerintah pusat maupun daerah. Padahal mereka sudah tinggal di area itu puluhan tahun. Lebih penting lagi, undang-undang dari pemerintah pusat itu hanya menyebut Paser, Dayak, dan Bugis sebagai pemilik tradisional area itu, dan tidak mengakui Kesultanan dan rakyat Kutai. Hal ini bisa menimbulkan perselisihan tanah, mengingat Kesultanan masih berwenang secara adat dalam mengelola tanah.
Marginalisasi rakyat asli bakal merugikan ibu kota baru Indonesia. Konflik antara rakyat asli setempat dan pendatang, khususnya mereka dari Jawa, bisa timbul. Aparat negara tingkat pusat, diperkirakan 1,5 juta orang, bakal menjadi kelompok pendatang yang dominan di Kalimantan Timur manakala kota baru itu sudah ada. Jumlah pendatang yang luar biasa besar ini berpotensi mengganggu ekonomi dan pasar lokal, khususnya dalam hal perumahan dan pangan. Kalau pemerintah tidak mengakomodasi kebutuhan penduduk setempat, hal ini bakal memicu konflik vertikal baru. Sebelumnya, konflik vertikal yang dikenal antara pemerintah pusat dan masyarakat di Aceh dan Papua telah menimbulkan pemberontakan yang berlangsung bertahun-tahun. Beberapa dari hal itu berfokus kepada isu tunggal pertambangan seperti minyak dan gas di Aceh serta pertambangan tembaga dan perak di Papua. Pada paruh kedua abad ke-320, kebijakan transmigrasi menimbulkan konflik horizontal antara pendatang dari Jawa dan penduduk lokal di sejumlah provinsi di luar Jawa. Karena itu, pelajaran yang harus diambil dari konflik-konflik terdahulu yang diakibatkan oleh pembangunanisme Orde Baru adalah bahwa mengakui hak tradisional atas tanah dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kompensasi yang adil bisa menyenangkan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Desain ibu kota baru menonjolkan “lingkaran” konsentrik dengan parlemen, kementerian, dan pemerintah menempat dua lingkaran pusat, kawasan bisnis di lingkaran kedua, dan area permukiman di lingkaran ketiga. Lokasi ibu kota baru juga beririsan dengan 162 konsesi tambah batu bara yang ada yang mencakup 203.720 hektare, tiga kali area Jakarta. Pemilik konsesi ini adalah konglomerat besar yang punya relasi erat dengan elite nasional. Para pemilik tambang juga melekat dengan lingkaran dalam politik di pemerintahan Jokowi. Hashim Djojohadikusumo, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, memiliki konsesi yang mencakup 173.395 hektare di lingkaran kedua, dan kepentingan bisnis Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memiliki tanah hampir 17.000 hektare di lingkaran kedua dan ketiga. Secara signifikan, sebagian besar perusahaan tambang ini mempunyai penambangan yang luas di sana. Ini meliputi 94 lubang tambang batu bara yang harus dipulihkan melalui ketentuan mengenai lingkungan.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) telah menggarisbawahi tidak adanya transparansi dan buruknya partisipasi publik dalam proses identifikasi tanah yang akan diberikan kepada pemegang konsesi sebagai pengganti konsesi yang telah diambil kembali. Ini berisiko mengasingkan dan menyingkirkan penduduk lokal yang tanahnya tersangkut dalam pertukaran itu, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Tapi kenyataan ini justru mendorong publik untuk percaya bahwa para konglomerat bakal dibebaskan dari tanggung jawab bagi reparasi dampak kerusakan lingkungan dari tambang mereka kalau mereka setuju mendukung secara finansial ibu kota baru. Ini, lagi-lagi, kontradiktif dengan visi dari kota yang mempromosikan pembangunan kota yang hijau dan berkelanjutan. Masa depan ibu kota Indonesia mungkin tak bakal lebih baik ketimbang Jakarta kalau ia dibangun di lingkungan yang berisiko dan rentan. Pertautan kepentingan antara bisnis dan politik harus ditolak dalam pembangunan ibu kota baru. Hal ini mendorong satu organisasi masyarakat sipil, Poros Nasional Kedaulatan Masyarakat (PNKM), mengajukan gugatan atas undang-undang ibu kota negara melalui Mahkamah Konstitusi. Mereka beralasan bahwa ibu kota baru bukan bagian dari proyek pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025, dan karenanya inkonstitusional.
Ringkasnya, gambaran utuh dari ibu kota baru Indonesia, masih bergantung kepada para elite ketimbang rakyat. Baru-baru ini, lebih dari 24.000 orang menandatangani sebuah petisi online menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena prihatin terhadap situasi Covid-19 dan defisit anggaran negara. Banyak kelompok menentang, khususnya mereka yang sudah tinggal di area tersebut. Mengakui keberadaan mereka dan mengakomodasi kebutuhan mereka adalah kunci untuk membangun ibu kota Indonesia yang inklusif bagi semua.
Selengkapnya: https://www.newmandala.org/a-new-indonesian-capital-city-conflict-pending/